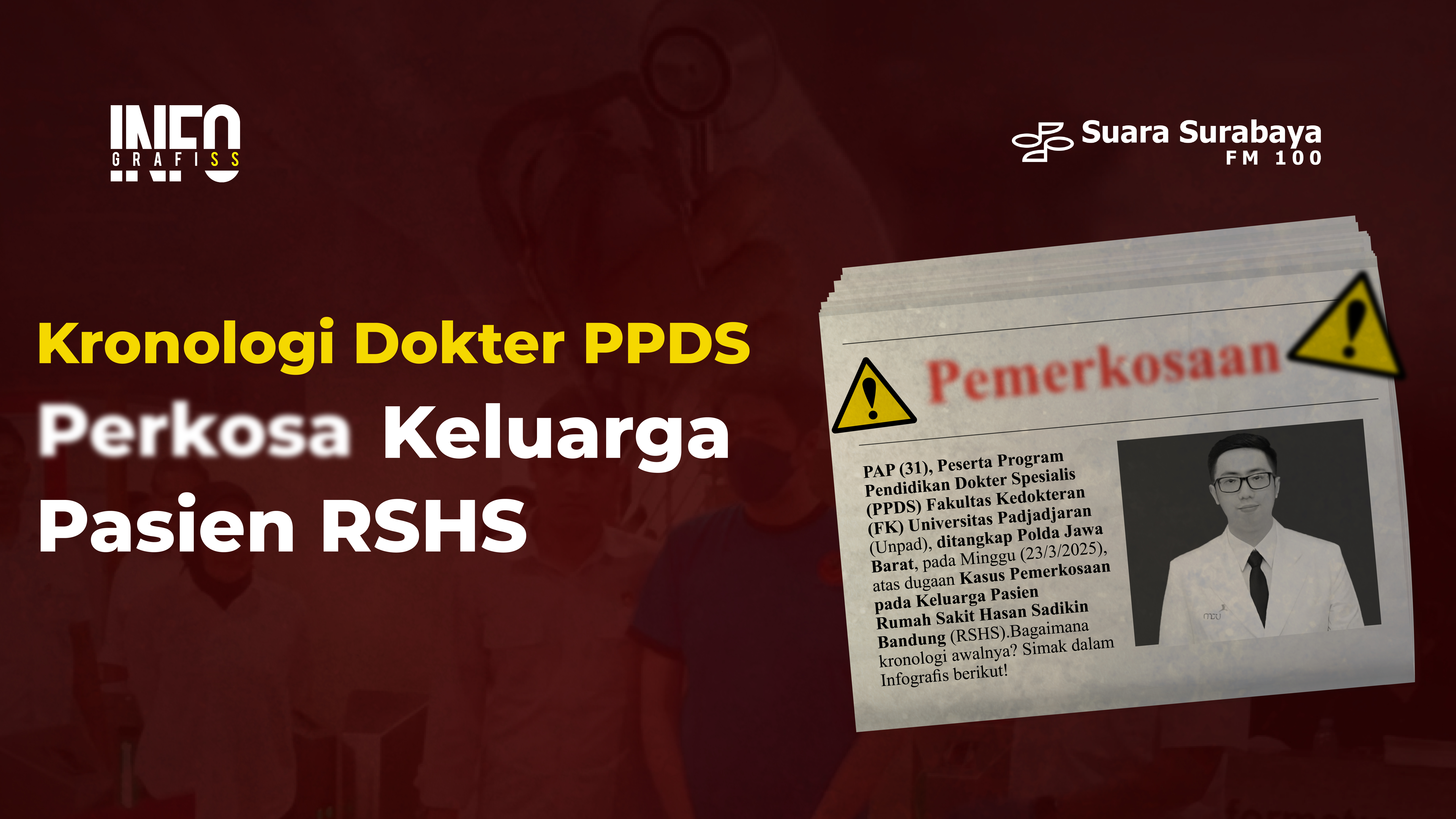Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengusulkan larangan eks koruptor atau mantan napi korupsi, untuk kembali mencalonkan diri di Pilkada. Usul ini disampaikan langsung Arief Budiman Ketua KPU kepada Joko Widodo Presiden RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019) kemarin. Pelarangan tersebut sudah tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Namun disisi lain, pada September 2018 lalu, PKPU tentang pelarangan napi korupsi untuk mengikuti Pilkada sebenarnya telah pernah diajukan. Namun, aturan tersebut berhasil dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) lantaran aturan PKPU itu bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu.
“Secara substansi MA sependapat dengan KPU, tapi secara norma harus diatur dalam UU, bukan di pelaksanaan (PKPU),” kata Abdullah Kepala Biro Hukum dan Humas MA di gedung MA, Jakarta, Senin (17/9/2019).
Tahun lalu, MA menolak PKPU karena bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.
Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi: Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
Untuk itu, Iqbal Felesiano Pakar Hukum Pidana Korupsi dan Media Unair mengatakan, jika KPU kembali ingin mengajukan gagasan pelarangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi kepala daerah, maka seharusnya diajukan menjadi Undang-Undang (UU) agar memiliki landasan hukum lebih kuat.
Karena menurutnya, aturan berbentuk PKPU masih berpotensi kalah di Mahkamah Agung seperti sebelumnya.
“Harusnya diatur di pasal perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak mudah dicabut, lebih kuat, dan meminimalisir adanya judicial review. Kalau cuma peraturan (PKPU, red) bisa kalah lagi di MA,” kata Iqbal kepada Radio Suara Surabaya, Selasa (12/11/2019).
Namun, untuk mengusulkan menjadi Undang-undang, lanjut Iqbal, KPU harus benar-benar memiliki persiapan yang lebih matang. Salah satunya dengan menyusun naskah akademik berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemilu dengan baik.
“Pihak pengusungnya, KPU, harus menyediakan naskah akademik yang bisa ditelaah lebih baik lagi,” ujarnya.
Kedua, menurutnya aturan tersebut akan dikabulkan jika ada keseriusan dari anggota legislatif, untuk mendukung pemberantasan korupsi.
“Kedua, harus melihat konteks di legislatif, apakah mereka mau mengubahnya menjadi lebih baik,” tambahnya.
Lalu yang ketiga, pentingnya dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama mengawal usul KPU tersebut. Dukungan yang besar dengan semua masyarakat bersuara mengenai isu ini, maka pemerintah akan mengetahui apa yang benar-benar menjadi keinginan masyarakat.
“Dukungan dari masyarakat yang cukup kuat, biar wakil rakyat ini menyuarakan suara rakyat, bukan suara mereka sendiri,” imbuhnya.
Menurutnya, pola-pola korupsi yang ada di Indonesia terutama disebabkan kualitas calon pimpinan buruk. Ditambah “ongkos politik” yang besar, membuat mereka berusaha untuk mendapatkan apa yang telah mereka keluarkan sebelum pemilihan.
“Mau tidak mau, kita harus sadar politik di Indonesia butuh biaya tinggi, dan mereka berusaha mengembalikan apa yang dikeluarkan,” kata Iqbal.
Ia berharap, sudah sepatutnya warga Indonesia berhak atas calon pemimpin yang berintegritas. Sehingga, pemerintah sudah sepatutnya membantu masyarakat dalam memilih wakilnya, dengan tidak memasukkan mantan napi korupsi sebagai calon wakil mereka.(tin/dwi)

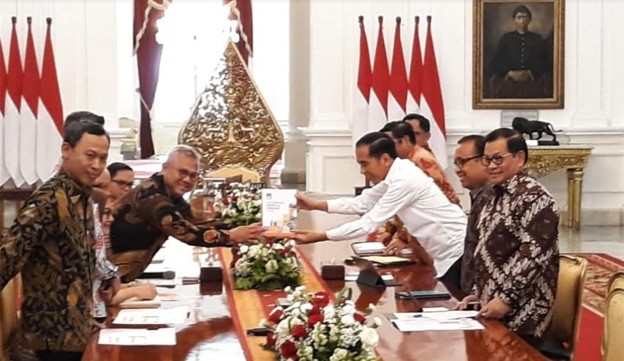
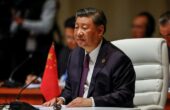




 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100