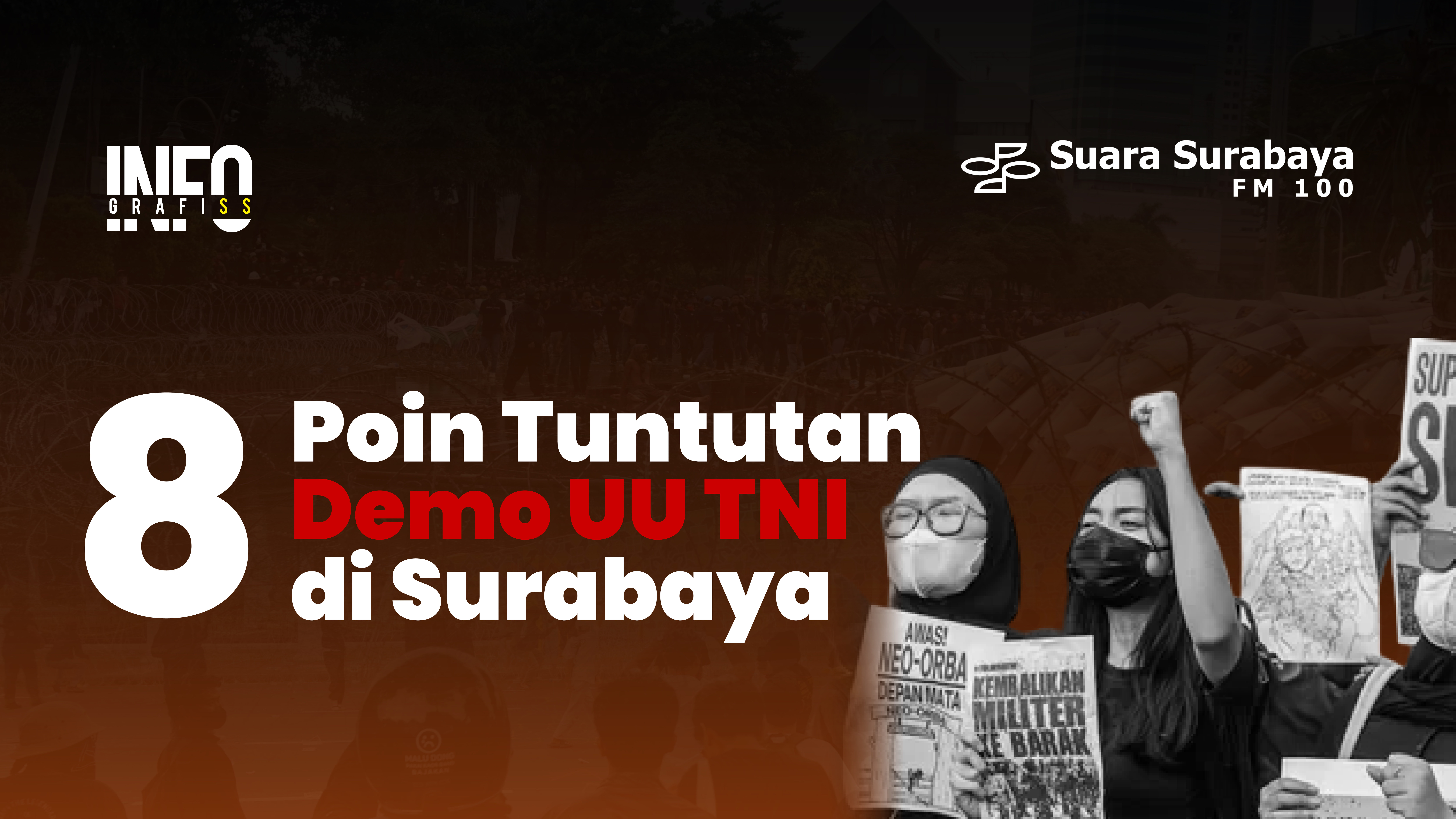Haidar Adam, ahli hukum tata negara Universitas Airlangga mengatakan, rangkap jabatan biasanya terkait dengan aspek jabatan publik. Ketika seseorang rangkap jabatan berarti memegang dua jabatan atau lebih, yang satu pasti terkait jabatan pemerintahan.
“Ada empat hal yang terkait dengan rangkap jabatan, yaitu kapasitas, integritas, netralitas, dan prioritas,” kata Haidar dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Rabu (22/2/2023).
Dia menjelaskan, terkait kapasitas, biasanya rangkap jabatan terdapat pengaturan yang spesifik di masing-masing organisasi yang menaungi. Pertanyaannya adalah sejauh mana yang bersangkutan memiliki kemampuan mengorganisasi diri, memastikan tugas, kewajiban, dan fungsi yang diemban tidak akan terganggu posisi atau kedudukan di institusi yang lain.
Kemudian terkait integritas, seringkali rangkap jabatan akan menempatkan seseorang pada posisi yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Setelah itu akan bisa diukur sejauh mana integritas pejabat bersangkutan.
Ketiga, aspek netralitas, biasanya terkait posisi jabatan publik yang seharusnya netral, tidak bias, tidak memihak.
Keempat, masalah prioritas. Ketika seseorang sudah ditempatkan di jabatan publik tertentu, dia harus bisa memprioritaskan kepentingan yang lebih banyak berimbas pada masyarakat yang lebih luas. Misalkan Menteri BUMN dan Ketua PSSI, tentu saja dimensi publik lebih nampak pada Menteri BUMN.
Dia melanjutkan, posisi menteri tentu tidak bisa kita lepaskan dari ketatanegaraan. Menteri merupakan bawahan presiden sehingga hak prerogatif presiden yang paling dominan dalam menilai apakah seseorang masih bisa menempati jabatan menteri itu atau diberhentikan.
“Kita juga tidak bisa menutup mata jika ada beberapa menteri yang juga menjadi ketua partai politik dan itu dibutuhkan presiden untuk mendapatkan dukungan politik. Makannya dalam pemerintahan terbagi dua, profesional dan politik. Menteri yang menjadi ketua umum partai politik lebih sibuk dari Ketua Umum PSSI,” ujar Haidar.
Secara aturan, kata Haidar, tidak ada ketegasan terkait rangkap jabatan untuk institusi di luar jabatan publik yang dilarang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU tersebut memang ada klausula dilarang merangkap jabatan pada institusi yang dibiayai negara dari APBD atau APBN. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah pembiayaan itu sepenuhnya atau separuhnya, sehingga membuka ruang penafsiran.
“Melihat praktek selama ini, hal semacam ini tidak jadi halangan. Uniknya UU Kementerian Negara jadi yang terpendek. Pasalnya beberapa saja, penjelasannya juga cukup jelas. Maknanya, ini menujukkan terkait hak prerogatif presiden yang tidak ingin diatur-atur. Ruang memilih yang besar untuk presiden,” ujar Haidar.
Jika publik menghendaki patokan yang jelas terkait rangkap jabatan, harus ada revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Terkait pasal larangan rangkap jabatan pada UU Kementerian Negara, pernah ada yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu dinyatakan tidak diterima karena MK menilai pemohon tidak cukup memiliki hak konstitusional sebagai pihak yang dirugikan. Namun dalam pertimbangannya MK menganggap rangkap jabatan seharusnya tidak boleh terjadi mengingat posisi menteri merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan publik.
“Dikhawatirkan rangkap jabatan akan menganggu tugas di institusi lainnya. Ditakutkan terjadi drama di kementerian,” ujarnya.
Hal lain yang perlu dicermati dan dikhawatirkan publik menurut Haidar, kontestasi 2024 semakin dekat. Biasanya pejabat publik melakukan kapitalisasi terhadap jabatan di luar kementerian yang sekiranya bisa meraup konstituen. Hal semacam ini juga tidak bisa dikaitkan dengan kode etik karena menteri ini bukan profesi, tidak memiliki kode etik untuk rujukan.
“Jabatan publik tergantung presiden. Sehingga partisipasi publik untuk mengkritisi menjadi penting. Jika terlalu banyak drama, akan teramplifikasi ke telinga presiden untuk melakukan evaluasi,” kata Haidar.(iss/rst)







 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100