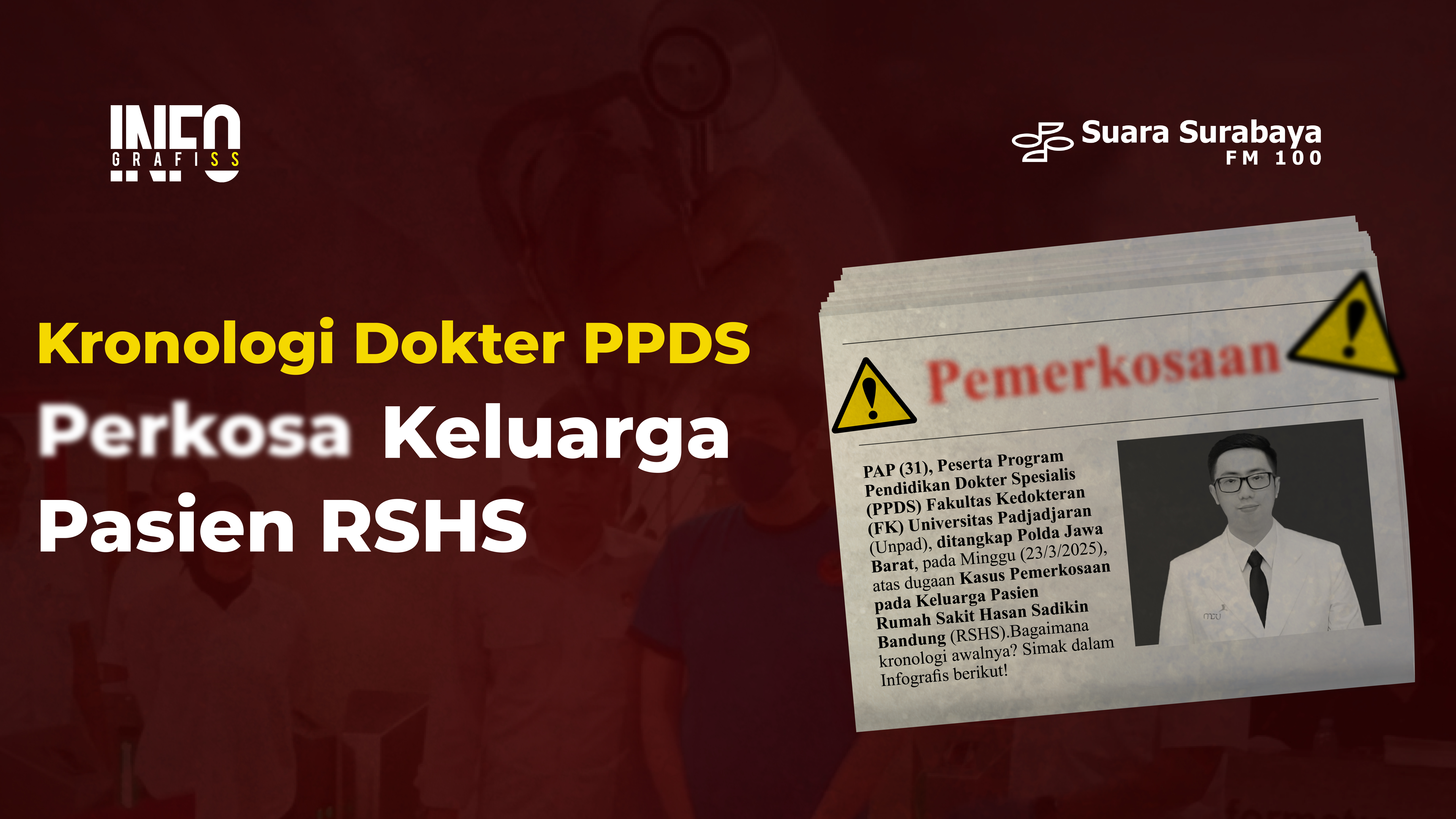Profesor Rachma Ida Guru Besar di bidang Media dari Universitas Airlangga membeberkan pandangannya mengenai model sekolah dan pengajaran yang akan terjadi saat era Metaverse tiba.
Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa era Metaverse adalah masa di mana muncul komunitas siber dan virtual 3D, tempat berlangsungnya aktivitas digital dengan avatar sebagai representasi user. Sehingga, seluruh kegiatan mulai dari berbelanja, bersosialisasi, bekerja hingga bersekolah, berlangsung dalam dunia fiksi virtual tersebut.
Perkembangan konsep Metaverse
Prof Ida bercerita, konsep metaverse awalnya muncul dari novel fiksi sains yang terbit pada tahun 1990an, saat itu konsep metaverse masih dianggap hanya seebagai imajinasi. Hingga akhirnya pada 2004, konsep tersebut diadopsi dalam sebuah gim bernama SimCity.
Konsep mengenai dunia virtual terus berkembang, hingga pada 2007 diadopsi oleh sebuah website secondlife.com yang menghadirkan avatar sebagai perwakilan user di dunia virtual.
“Saat itu yang saya mainkan avatar, jadi saya direpresentasikan di avatar. Avatar itu bebas berkeliaran di cyber space. Untuk mengakses ini, butuh teknologi yang tidak mudah saat itu. RAM-nya harus besar,” kata Prof. Ida kepada Radio Suara Surabaya, Senin (10/1/2022).

User dapat menggunakan avatar di dunia digital menggunakan identitas yang berbeda dengan kehidupan nyata. Di era metaverse, avatar atau pemain di dunia digital dapat beraktivitas layaknya di dunia nyata seperti berinteraksi, bersekolah dan melakukan transaksi digital dengan mata uang kripto.
“Ciri masuk ke metaverse, identias kita di real world sudah tidak ada lagi. Ketika saya menciptakan avatar bisa apa saja. Bisa jenis kelamin berbeda, bahkan wajah yang sangat berbeda,” jelasnya.
Metaverse dan Sistem Pendidikan
Menurut Prof. Ida, akan muncul berbagai peluang sekaligus tantangan besar jika metaverse sudah melingkupi sistem pendidikan dan sekolah. Dilihat dari peluang, pendidikan di era metaverse akan menghadirkan pengalaman yang berbeda.
Kemudian metaverse yang bersifat borderless atau menyediakan ruang tak terbatas, memunculkan engagement yang lebih besar yang harus dihadapi.
“Kalau pendidikan masuk ke metaverse, maka kita harus siap dengan international engagement yang lebih luas, yang benar-benar wild. Orang siapapun masuk, bisa. Meski kita bisa mengunci beberapa ruang (digital),” jelasnya.
Untuk itu, Prof Ida mengingatkan masyarakat tentang dampak masuknya pendidikan di era metaverse yang perlu diantisipasi.
Pertama, karena kehadiran user di dunia virtual direpresentasikan dengan avatar, maka manusia berpotensi untuk sibuk mengawasi aktivitas avatar setiap waktu dan mengurangi aktifitas di dunia nyata.
“Kita nggak akan bisa tidur karena mengikuti avatar. Seperti Tamagotchi, mulai dari telur, vetus dan terus tumbuh besar. Kalau nggak dikasih makan akan mati. Begitu juga avatar, kalau nggak dikelola akan wild (buas), dia akan pergi kemana-mana,” ungkapnya.
Tantangan kedua, yakni mengenai jaminan keamanan siber seiring aktivitas digital yang lebih kompleks. Sehingga kebutuhan terhadap internet engineer akan semakin dibutuhkan di masa depan.
“Cyber security harus dipikirkan bagaimana keamanan untuk membuat aturan-aturan atau software keamanan untuk itu. Karena setiap ada cyber security, pasti ada ahli cyber construction. Yang dibutuhkan nanti adalah internet engineer yang kita sebut sebagai constructor tadi,” kata Prof. Ida.
Tantangan ketiga, yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membuat tidak semua orang mampu mendapatkan akses di era metaverse. Ia menceritakan, dalam sebuah kuliah daring saja, beberapa mahasiswanya masih mengeluhkan sinyal yang membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat.
Dampak lainnya, yakni hilangnya proses interaksi langsung antara pengajar dan murid karena interaksi lebih banyak berlangsung secara virtual.
“Maka, angka pendidikan menjadi mahal dan interaksi manusia akan hilang. Padahal pendidikan tidak hanya soal materi, tapi juga message education seperti etika logika berfikir yang tidak bisa diajarkan secara virtual,” imbuhnya.
Belum lagi persoalan hukum siber, yang saat ini, belum menjadi solusi dari kemungkinan-kemungkinan kejahatan siber yang terjadi di dunia virtual.
“Contoh kecil saja, apa yang akan dilakukan saat avatar kita mengalami pelecehan seksual? Bagaimana cyber police akan mengajar avatar tadi? Cyber law harus dipikirkan. Di Amerika saja, saat ini masih gagap mengatur itu,” ungkapnya.
Dia juga menyarankan jika nantinya, era metaverse membuat pendidikan memasuki sekolah-sekolah virtual, maka orangtua sudah harus menyiapkan teknologi mumpuni agar anak-anak mereka dapat mengikuti sistem pengajaran dengan baik.
Kedua, orangtua juga harus memperhatikan menejemen waktu anak-anak mereka, agar tidak ‘tenggelam’ terlalu dalam dalam dunia metaverse.
“Seperti kapan student time, kapan bermain, kapan waktu ke luar, kapan waktu bersama keluarga, dan kapan waktu bersosialisasi di dunia nyata,” ujarnya.
Ketiga, adanya perangkat aturan untuk meminimalisir terjadinya plagiarism yang berpotensi besar terjadi di era metaverse yang borderless (tanpa batas).
“Materi-materi dalam metaverse harus disiapkan karena sudah open access. Itulah yang dihadapi salah satunya mencegah plagiarisme,” papar Prof. Ida.
Keempat, yakni masuknya ekonomi politik di dunia pendidikan yang harus diantisipasi dengan baik.
Realitas yang berbeda dan aktivitas virtual yang berkembang pesar, menurut Prof. Ida, membuat kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi era metaverse harus dikaji ulang. Mengingat kesiapan SDM, teknologi, dan infrastuktur lainnya yang masih perlu dikembangkan.
“Kemarin pemerintah mengatakan, organisasi harus siap dengan metaverse. Metaverse itu tidak gampang, harus diajari dulu, masuk dulu. Seminggu di situ, how do you feel? kalau menyenangkan berarti tidak ada masalah,” ungkapnya. (tin/rst)



 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100