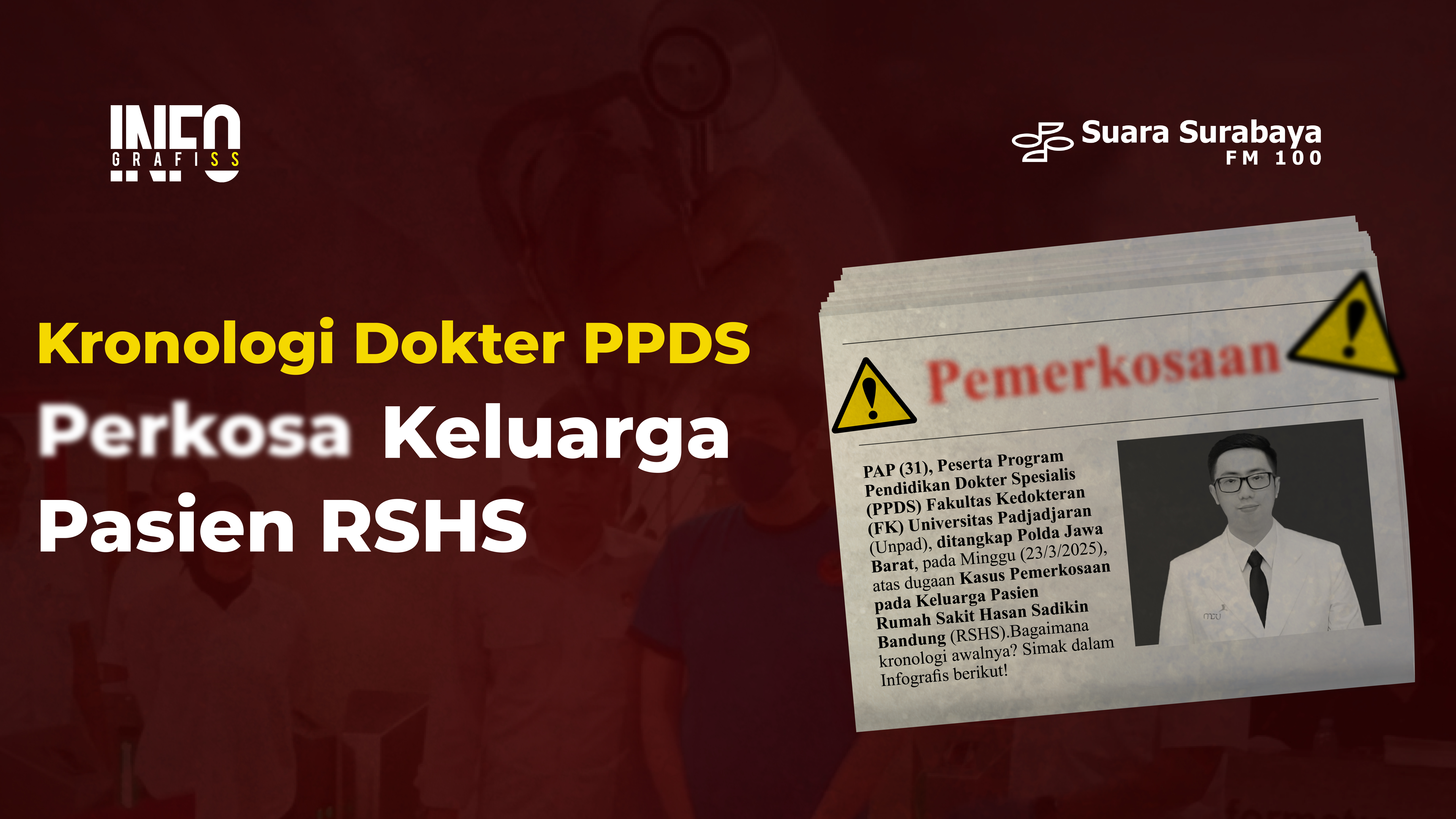Haidar Adam, pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga mengatakan, sebagian besar pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur proteksi terhadap transaksi bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik dan kebebasan warga negara untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi.
“Hak konstitusional warga negara terhadap informasi, tidak lepas dari konsep awal hak kebebasan berekspresi,” kata pengajar Hukum Hak Asasi Manusia ini dalam acara live talkshow KelaSS Pintar “Polemik Pasal Karet UU ITE”, Rabu (24/2/2021).
Adam menjelaskan, ada dua alasan mengapa hak memperoleh informasi harus dilindungi. Pertama, interdependensi. Hak mendapatkan informasi sangat esensial karena berkaitan dengan hak lainnya. Contohnya hak mendapat pendidikan dan layanan kesehatan.
Kedua, kebebasan hak memperoleh informasi dapat menjadikan masyarakat semakin progresif. Pola pikir masyarakat yang kritis, dapat membuat peradabannya semakin maju.
“Kalau keberadaan UU ITE menghapus potensi masyarakat adu pendapat apalagi ketika sasaran kritiknya adalah pemerintah, justru akan merepresi, menindas ruang kebebasan yang akhirnya merugikan peradaban masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Perdebatan mengenai UU ITE yang mengemuka akhir-akhir ini terjadi karena beberapa pasal yang kerap kali digunakan dalam kasus terkait kritik dan pencemaran nama baik.
Dalam Pasal 27 ayat 3 ada ketentuan mengenai larangan untuk melakukan tindakan penghinaan. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
“Ini pasal yang paling mudah diterapkan karena jejak digital abadi di internet dan bisa dijadikan bukti. Ketika orang tersinggung dengan ucapan orang lain di media sosial, dia bisa melaporkan orang itu. Kemudian oleh polisi hal semacam itu diproses. Ini sangat terkait dengan literasi digital dan tingkat kedewasaan masyarakat menggunakan media sosial,” kata Adam.
Menurutnya, idealnya masalah pencemaran nama baik dan penghinaan harus diselesaikan secara bertahap, tidak sekadar lapor tangkap. Misal sudah adakah mediasi atau permintaan maaf. Harus terbuka ruang untuk itu.
Ini juga berkaitan dengan karakter atau sifat dasar hukum pidana yaitu ultimum remedium atau tahap terakhir. Jika semua tahapan lain tidak berhasil, pidana baru dijalankan. Seperti di negara lain, Eropa misalnya, pencemaran nama baik masuk ke perdata, bukan pidana. Tuntutannya ganti rugi.
Tentang tingkat keberhasilan UU ITE memproteksi kehormatan martabat pribadi seseorang. Adam mengutip teori Lawrence M. Friedman. Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga faktor, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).
Dari faktor substansi hukum, apakah ada materinya jelas, klir, tidak multitafsir. Lalu apakah adil, tidak diskriminasi.
Dari faktor struktur hukum, aparat hukumnya juga harus bagus. Ada dua kata kunci yaitu kompetensi dan integritas. Aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan dan kecakapan sehingga dia bisa memahami aturan hukum itu
“Hukum sifatnya tidak statis. Meski relatif lama, tidak menutup kemungkinan hukum itu direvisi. Nyatanya beberapa UU juga direvisi. Apakah UU ITE yang baru memberikan peluang membungkam atau memproteksi, itu jadi tugas kita bersama untuk memperbincangkan.”
Beda Kritik dan Penghinaan
Adam menegaskan, kritik dan penghinaan bisa dibedakan dengan klir. Rakyat boleh dan bahkan harus mengkritik kinerja atau kebijakan pemerintah ketika tidak sesuai kampanyenya. Yang tidak boleh menghina pribadinya. Misal menyebut sebagai binatang atau sesuatu yang tidak sesuai realita.
“Kalau mau mengkritik sasar kebijakannya, bukan kepribadian orang tersebut kecuali berkaitan dengan kebijakannya misal bermewah-mewah tapi profil gajinya tidak sesuai, rakyatnya miskin, tidak bisa mengakses pendidikan dan kesehatan, tidak apa dikritik. Sebutkan jabatannya, jangan sebutkan nama. Itu tidak apa-apa,” ujar Adam.
Kemudian terkait batasan penghinaan, menurut dia, tergantung aparat hukum dan UU-nya jelas atau tidak. Salah satu pasal yang problematis dan berpotensi multitafsir adalah pasal 28 ayat 2.
Pasal 28 ayat 2 UU ITE menyebutkan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
“Ketentuan dalam pasal 28 problematis karena seringkali kritik terhadap agama melahirkan tuntutan hukum. UU penodaan agama juga masih berlaku. Padahal kita lihat setiap agama kan mengklaim kebenaran. Kecuali kalau ada seseorang yang menghasut orang lain dengan mendasarkan pada kebencian agama tertentu, seperti hasutan untuk membunuh. Tapi kalau kritik terhadap agama, sudah keniscayaan karena esensi agama adalah klaim kebenaran,” kata dia.
“Batasannya, kalau mengkritik agama tidak apa-apa tapi kalau menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap suku, agama, ras, golongan tertentu, itu yang tidak diperbolehkan,” tambahnya.
Adam mengingatkan masyarakat harus waspada dengan apa yang dikritik, jangan sampai jatuh ke dalam pencemaran nama baik.
“Dalam demokrasi digital saat ini, pertama kita harus sadar terhadap hak-hak kita. Kita boleh mengekspresikan pendapat. Kedua, sebelum membagikan informasi, harus waspada terhadap informasi yang dibagikan. Ungkapan mulutmu harimaumu, jadi jemarimu harimaumu. Hati-hati, lebih bijak menggunakan sosial media. Negara jangan tipis kupingnya kalau dikritik. Dengarkan dulu, kalau tidak benar bisa di-counter dengan info tandingan. Dengan demikian, kita bisa bahu membahu mewujudkan iklim dunia digital yang lebih sehat dan progresif,” ujarnya.(iss/lim)







 NOW ON AIR SSFM 100
NOW ON AIR SSFM 100